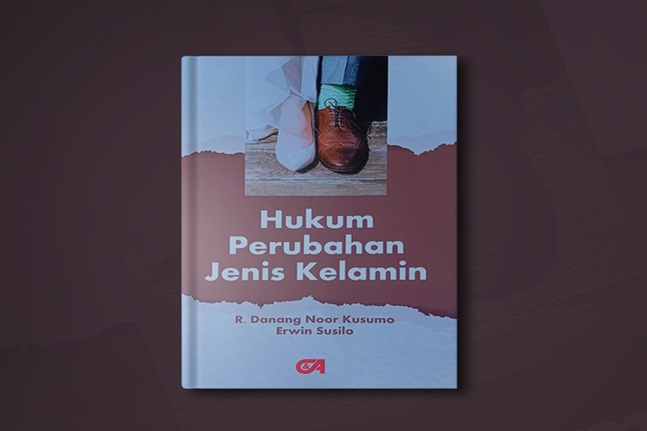Perubahan jenis kelamin hampir selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Orang yang berusaha mengganti jenis kelaminnya dianggap berusaha melawan kodrat. Terlepas dari perbedaan pandangan di masyarakat, hakim harus memberikan jalan keluar jika permohonan ganti jenis kelamin masuk ke pengadilan.
Bukankah ada maksim hukum dalam bahasa Latin, lex semper dabit remedium, yang bermakna hukum selalu memberikan solusi/obat. Hakim-hakim di Indonesia pun sudah familiar dengan pernyataan bahwa hakim dilarang mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Judex debet judicare secundum allegata et probate: hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta dan argumentasi yang diajukan para pihak yang berperkara.
Perkara perubahan jenis kelamin mungkin dapat dijadikan contoh. Peraturan perundang-undangan masih terasa sumir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak terlalu detail mengatur perubahan jenis kelamin. Norma yang diatur pada umumnya berkaitan dengan pencatatan perubahan jenis kelamin.
Setidaknya, begitulah kondisi yang melatarbelakangi dua orang hakim menulis buku “Hukum Perubahan Jenis Kelamin”, yang kini ada di hadapan pembaca. Kedua penulis adalah R. Danang Noor Kusumo, dan Erwin Susilo. Kusumo tercatat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan Susilo tercatat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sigli.
Sedikit banyak, buku ini bercerita pengalaman penulis memeriksa dan memutus permohonan perubahan jenis kelamin. “Penulis membuat buku ini karena pengaturan mengenai perubahan jenis kelamin masih sumir,” tulis mereka dalam Kata Pengantar.
“Perubahan jenis kelamin” adalah istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan. Ada namanya peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lalu, ada juga istilah peristiwa penting lainnya. Sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, perubahan jenis kelamin masuk kategori peristiwa penting lainnya.
Meski demikian, perubahan jenis kelamin tak hanya terjadi setelah UU Adminduk lahir. Jauh sebelumnya, sudah ada permohonan perubahan jenis kelamin yang masuk ke pengadilan. Pada 1973, misalnya, seorang warga negara Indonesia melakukan operasi perubahan kelamin di Singapura.
Setelah kembali ke Indonesia, yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pengadilan bukan saja mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, tetapi juga meminta pengesahan atas perubahan namanya.
Di tengah kekosongan peraturan perundang-undangan saat itu, hakim mengabulkan permohonan dengan mengeluarkan (dulu menggunakan istilah) penetapan. Dalam pertimbangannya, hakim memaparkan fakta bahwa perundang-undangan memang tidak mengatur materi permohonan, tetapi pengadilan harus menjawab status hukum pemohon. Hakim perlu menunjuk pada asas-asas hukum yang berlaku umum.
Dalam perkara tersebut, hakim tidak menggunakan instrumen hukum karena memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (hal. 24).
Ini bukan perkara pertama permohonan jenis kelamin yang masuk dan diputus pengadilan Indonesia. Ada beberapa kasus yang menarik dan membuka ruang diskusi publik. Tetapi, sebelum beranjak lebih jauh, penting diingatkan bahwa buku ini bukan tentang kasus-kasus perubahan jenis kelamin.
Buku terbitan Citra Aditya Bakti Bandung ini lebih layak dianggap sebagai pedoman tentang bagaimana sikap hakim ketika diberi tugas memeriksa perkara perubahan jenis kelamin, dan aspek-aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin.
Maka, tidak mengherankan, bab pertama berisi uraian tentang gugatan contentiosa dan gugatan voluntair. Ini penting karena kesalahan menggunakan jenis upaya hukum dapat berimplikasi yuridis, yang membuat pekerjaan sia-sia (hal. 10).
Selebihnya, buku ini menguraikan hukum acara permohonan perubahan jens kelamin, tak tak jauh berbeda dari hukum acara perdata pada umumnya. Ada hal-hal yang perlu dianalisis hakim baik tahap pra persidangan maupun tahap persidangan. Jika permohonan dinilai memenuhi syarat, maka hakim mengeluarkan penetapan atas permohonan. Contoh penetapannya ada di dalam buku ini.
Kehadiran karya Kusumo dan Susilo ini layak diapresiasi, terutama berguna mempermudah hakim menangani permohonan perubahan jenis kelamin. Kalau Anda berpikir buku ini memuat perdebatan etika, media, dan religi mengenai perubahan jenis kelamin, sebaiknya pikiran tersebut dihilangkan dulu. Anda perlu membaca literatur lain yang lebih fokus dan spesifik.
Tetapi, jika membayangkan buku ini juga hanya mengenai hukum acara (prosedur), Anda juga salah. Sebab, buku ini juga menguraikan aspek-aspek apa saja yang perlu dibuktikan saat mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin. Bukankah masyarakat pada umumnya, dan lawyer pada khususnya, membutuhkan uraian mengenai aspek-aspek dimaksud?